Menuju Makna Baru Sang Bumi Ruwa Jurai
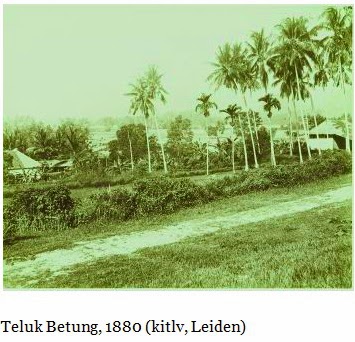
Oleh M. Syahran W. Lubis
SANG Bumi Ruwa Jurai. Itu semboyan Provinsi Lampung. Pada perkembangannya, ada pula yang menyebutkannya sebagai Sai Bumi Ruwa Jurai. Merujuk kepada pelafalan lokal, penulisan seharusnya Sang Bumi Khuwa Jukhai atau Sang Bumi Ghuwa Jughai. Artinya, Satu Bumi Dua Cabang.
Ada yang memaknai semboyan itu sebagai Lampung yang terdiri dari Pesisir dan Pepadun. Ada pula yang memaknainya sebagai Lampung terdiri dari etnis asli dan pendatang.
Berkaitan dengan makna yang kedua ini, saya kerap kali berpikir yang mana suku asli Lampung. Masalahnya, sampai sekarang setidaknya saya memahami ada empat asal muasal suku Lampung, yang saya rangkum dari “cerita yang masuk akal” dan pengakuan beberapa orang Lampung yang saat ini pun masih hidup.
Bagi sebagian orang Tapanuli, Ulun (Orang) Lampung berasal dari tanah Batak, yakni melalui Ompung Silamponga yang terdampar di pesisir barat Lampung, tepatnya di wilayah yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Sekalabrak.
Kesamaan makna sejumlah kata yang digunakan oleh dua etnis ini memaksa saya untuk memercayai teori bahwa (setidaknya) sebagian orang Lampung berasal dari tanah Batak.
Beberapa kata bermakna sama itu di antaranya “ulu” (kepala), “ipon” (gigi), “igung/ighung” (hidung), “lading” (pisau/senjata tajam/pedang), dan “jolma/jelma” (manusia). Begitu pula dengan kata “botong/butong” yang bermakna kenyang (betong dalam bahasa Lampung juga bermakna perut atau kenyang, butong dalam bahasa Lampung berarti marah), dan “modom/pedom” yang bermakna tidur.
Sekitar 15 tahun lalu, saya membeli sebuah buku tentang asal-usul orang Lampung dan di dalamnya menuliskan bahwa profesor dan pakar hukum adat, serta juga budayawan, yang sangat dihormati di Lampung, Hilman Hadikusuma, termasuk yang menyatakan sebagian suku Lampung berasal dari Ompung Silamponga.
Ada pula keyakinan bahwa sebagian orang Lampung adalah keturunan Tionghoa, tetapi telah melalui proses asimilasi (pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru) selama ratusan—bahkan mungkin ribuan—tahun.
Profesor Hilman Hadikusuma kembali disebutkan sebagai salah seorang pendukung teori ini. Disebutkan bahwa kata Lampung itu berasal dari kata To-lang-po-hwang yang berarti orang Lampung. Penyebutan ini pun mendekati nama kerajaan Tulang Bawang di bagian timur laut Provinsi Lampung saat ini.
Secara faktual, dengan sangat mudah kita menyaksikan banyak orang Lampung—juga sebagian suku di Sumatera Selatan—yang memiliki kemiripan wajah terutama bagian mata dengan etnis Tionghoa.
Teori ketiga dan keempat asal-usul orang Lampung ialah keturunan Bugis Makassar dan Banten. Ini bukan teori lama yang berusia ratusan hingga mendekati ribuan tahun, tetapi yang mengaku demikian pun masih hidup. Beberapa orang Lampung yang mengaku keturunan Bugis Makassar dan Banten ini mengaku masih bisa menelusuri garis keturunan mereka yang berasal dari Bugis Makassar dan Banten.
Menyimak empat teori tadi, kembali lagi saya berpikir dan bertanya: yang mana sesungguhnya orang Lampung asli?
Pada satu titik, saya berkesimpulan bahwa orang Lampung yang sekarang disebut sebagai asli pun merupakan proses asimilasi dari beberapa suku pendatang.
Asimilasi Makna Baru
Pada saat ini, saya berpendapat Lampung berada di awal proses asimilasi tahap kedua. Sang Bumi Khuwa Jukhai sedang berada dalam proses pembentukan “makna baru”.
Pada asimilasi pertama beratus tahun yang lalu, orang-orang pendatang hadir di Lampung dan menjalani proses panjang sehingga dapat dikatakan sama sekali kehilangan identitas suku aslinya.
Sejak awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1905, program transmigrasi dimulai ke Bagelen, desa yang sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pringsweu.
Saya melihat ini merupakan titik mula dari proses asimilasi tahap kedua yang bakal berjalan panjang yang semestinya membentuk makna baru Sang Bumi Ruwa Jurai.
Pada tahun 1963, gelombang kedua yang menjadi titik berikutnya dalam proses pembentukan makna baru itu adalah kedatangan orang-orang Bali yang mengungsi akibat Gunung Agung meletus dengan dahsyat. Saat ini, orang-orang dari Bali yang bermukim di Lampung, merujuk pada sejumlah literatur, telah mencapai setidaknya 1,3 juta orang.
Proses asimilasi pertama yang melalui perjalanan panjang hingga ratusan tahun telah memunculkan “orang asli Lampung” yang bahkan sudah tidak lagi memiliki rekam jejak etnis mereka yang terdahulu.
Makna baru Sang Bumi Ruwa Jurai yang saya harapkan terwujud sebagai akhir—lebih tepatnya tiba di satu titik penting, karena sebuah proses sesungguhnya tidak pernah akan berakhir—sebagai bagian asimilasi tahap kedua adalah semua pendatang di Lampung merasa dia di satu sisi sepenuhnya orang Lampung, tetapi di sisi lain dan pada saat bersamaan, dia tetap mampu mempertahankan akar budaya asalnya.
Jujur saja, saya melihat proses akulturasi (percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi) etnis pendatang dengan etnis asli di Lampung ‘kalah jauh’ dibandingkan dengan yang telah terjadi di Sumatera Utara.
Wilayah Deli di Sumatera Timur, yang sekarang menjadi bagian dari Sumatera Utara, pada tahun 1890 hingga 1920—dimulai sekitar 15 tahun sebelum program transmigrasi ke Lampung—kedatangan orang dari Pulau Jawa dalam gelombang besar.
Sayangnya, tidak ada literatur yang menyebutkan secara pasti jumlah orang dari Pulau Jawa yang ke Deli untuk dipekerjakan membuka perkebunan-perkebunan—terutama tembakau—yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda atau dibangun swasta asing yang didukung oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Di Sumatera Utara, orang-orang Jawa telah menjelma menjadi Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera) yang memiliki karakter yang sangat mirip dengan etnis setempat, sedangkan di Lampung, perkampungan Jawa didominasi oleh budaya yang masih sangat kental dengan daerah asal mereka.
Alangkah indahnya apabila makna baru Sang Bumi Ruwa Jurai dimaknai dengan orang-orang pendatang yang sepenuhnya merasa sebagai orang Lampung walaupun di sisi lain tetap bangga dan mempraktikkan budaya dengan asal-muasalnya.
Lampung mempunyai beberapa budayawan yang kelampungannya tak diragukan dan pada saat yang sama tidak pula kehilangan identitas suku aslinya. Menurut saya, Lampung layak bangga memiliki Christian Heru Cahyo Seputro atau Budi Hutasuhut yang bisa sebut sebagai contoh etnis pendatang yang telah teruji kelampungannya.
Lebih ke belakang lagi, Lampung punya tokoh Mr. Gele Harun (almarhum) yang sejatinya berasal dari etnis Tapanuli, tetapi masyarakat Lampung sudah sangat lekat dengannya dan “lupa” bahwa beliau bermarga Nasution dan lahir di Sibolga, Sumatera Utara.
Saya berharap asimilasi tahap kedua betul-betul mampu mewujudkan kaum pendatang merasa 100 persen sebagai orang Lampung—dengan menjalankan segenap identitas kelampungannya, termasuk budayanya—dan pada saat yang bersamaan juga tetap bangga memelihara identitas etnis asalnya.
Itu akan menjadi makna baru Sang Bumi Ruwa Jurai. Saya sendiri, meskipun tidak lagi bermukim di Lampung, selalu berharap bisa menjadi bagian dari proses menuju makna baru itu. Semoga! []
- Ditulis untuk buku Mencari Lampung dalam Senyapnya Jalan Budaya: Kado 50 Tahun Udo Z Karzi (dalam proses terbit).