Belajar Menulis Puisi
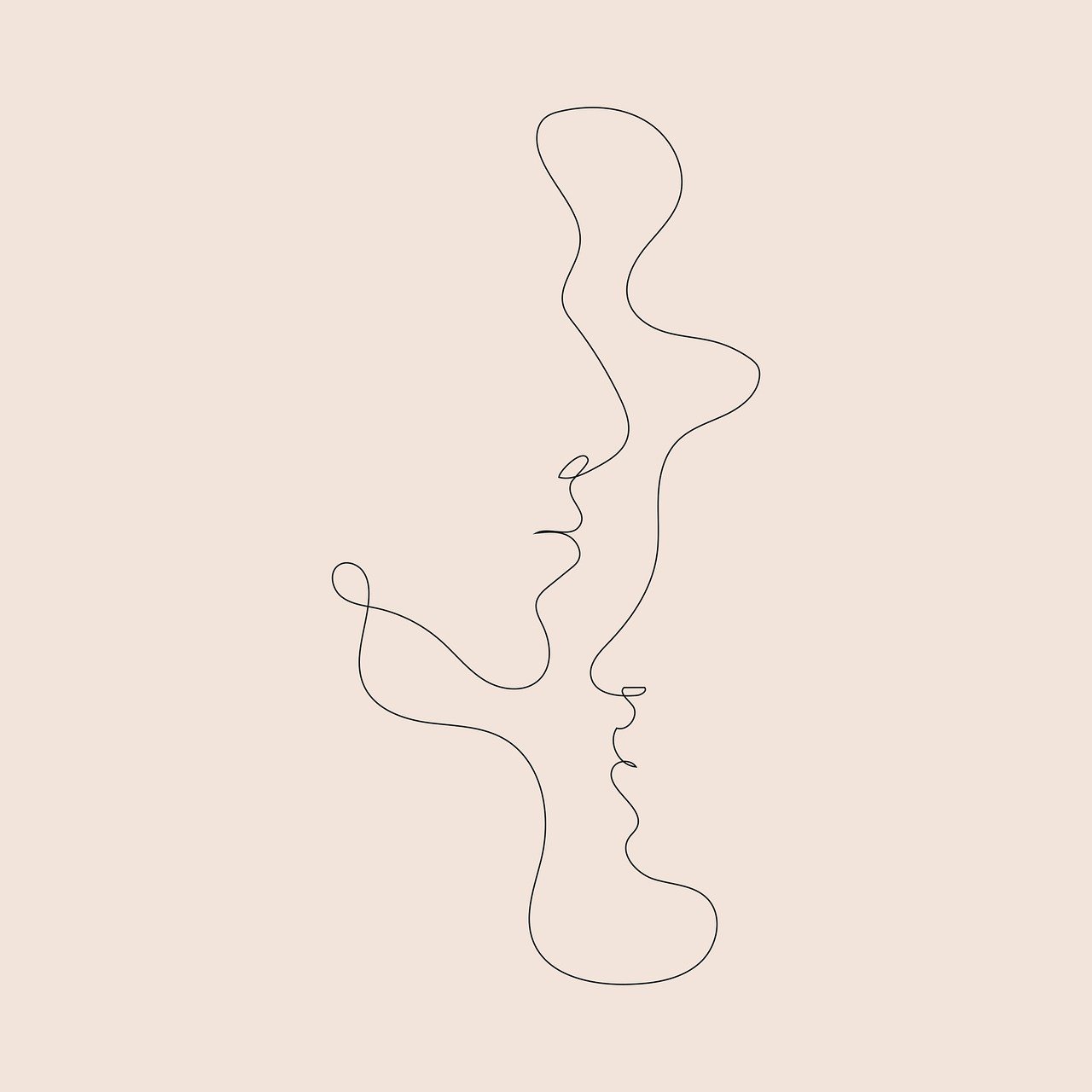
“SELAIN bahasanya yang bahasa Lampung, apa yang hendak Anda tawarkan dengan puisi-puisi ini? Adakah bedanya dengan puisi yang berbahasa Indonesia?” gugat seseorang setelah membaca Momentum: Kumpulan Sajak Dwibahasa Lampung-Indonesia (2002).
Kapok gua!
Benaran. Berat amat tugas penulis puisi yang harus membawa suatu nilai, konsep, teori, filosofi, dll dalam karyanya. Tidak. Saya sedari mula menulis puisi ya menulis saja setelah “mabok” membaca aneka rupa puisi dari para penyair terkemuka, baik lokal, nasional maupun dunia.
Sebalnya, si pengkritik, ternyata tak fasih berbahasa Lampung. Ia hanya membaca yang berbahasa Indonesianya. Harusnya tak usah saya pikirkan. Tapi, saya sudah telanjur mutung.
Maka, setelah itu, lahir lagi buku puisi Mak Dawah Mak Dibingi (2007) dan Setiwang (2020). Keduanya berbahasa Lampung.
Kebanyakan orang di Lampung tidak mengerti. Biarin! Beberapa pihak–termasuk Pemimpin Umum Harian Lampung Ekspres Plus (alm) Harun Muda Indrajaya dalam sebuah acara di kantor redaksinya–menganjurkan agar buku puisi saya itu dibuat dwibahasa Lampung-Indonesia lagi. Tapi, saya tetap ogah.
Menulis puisi berbahasa Indonesia pun saya hanya sesekali. Biasanya untuk keperluan tertentu. Misalnya, diminta atau karena tertarik dengan tema tertentu. Bahkan, (alm) Ahmad Yulden Erwin bilang, “Yang saya tunggu darimu: buku puisi. Bahasa Indonesia! Bahasa Lampung mana saya ngerti.”
Saya cengengesan saja.
Kesekian kalinya saya “patah arang” dengan makhluk bernama puisi.
Sebelum lebih lanjut, saya mau kisahkan serbasedikit perkenalan saya dengan puisi.
***
Ketimbang prosa, mulai dari dongeng, cerita rakyat, cerita anak, cerita pendek, cerita bersambung, novelet hingga novel dan roman; makhluk bernama puisi belum begitu akrab dengan saya ketika masih di kampung. Puisi itu sesuatu yang tidak mudah ‘dibecandai’. Hanya ada beberapa jenis puisi yang saya sukai saat masih SD-SMP. Misalnya, pantun jenaka seperti ini:
gendang
gendut
tali kecapi
kenyang perut
senanglah hati
Lalu, ada soneta berjudul “Menyesal” karya A. Hasjmy:
Pagiku
hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Kini petang datang membayang
Batang usiaku sudah tinggi
Aku lalai di
hari pagi
Beta lengah di masa muda
Kini hidup meracun hati
Miskin ilmu, miskin harta
Ah, apa guna
kusesalkan
Menyesal tua tiada berguna
Hanya menambah luka sukma
Kepada yang
muda kuharapkan
Atur barisan di hari pagi
Menuju arah padang bakti.
Atau, puisi yang bercerita semacam karya WS Rendra:
Balada Terbunuhnya Atmo Karpo
Dengan
kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi
Bulan berkhianat gosok-gosokkan tubuhnya di pucuk-pucuk para
Mengepit kuat-kuat lutut menunggang perampok yang diburu
Surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang
Segenap
warga desa mengepung hutan itu
Dalam satu pusaran pulang balik Atmo Karpo
Mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang
Berpancaran bunga api, anak panah di bahu kiri
Satu demi
satu yang maju terhadap darahnya
Penunggang baja dan kuda mengangkat kaki muka.
Nyawamu barang pasar, hai orang-orang bebal!
Tombakmu pucuk daun dan matiku jauh orang papa.
Majulah Joko Pandan! Di mana ia?
Majulah ia kerna padanya seorang kukandung dosa.
Anak panah
empat arah dan musuh tiga silang
Atmo Karpo tegak, luka tujuh liang.
Joko Pandan!
Di mana ia!
Hanya padanya seorang kukandung dosa.
Bedah
perutnya tapi masih setan ia
Menggertak kuda, di tiap ayun menungging kepala
Joko Pandan!
Di manakah ia!
Hanya padanya seorang kukandung dosa.
Berberita
ringkik kuda muncullah Joko Pandan
Segala menyibak bagi derapnya kuda hitam
Ridla dada bagi derunya dendam yang tiba.
Pada langkah pertama keduanya sama baja.
Pada langkah ketiga rubuhlah Atmo Karpo
Panas luka-luka, terbuka daging kelopak-kelopak angsoka.
Malam bagai
kedok hutan bopeng oleh luka
Pesta bulan, sorak sorai, anggur darah
Joko Pandan
menegak, menjilat darah di pedang
Ia telah membunuh bapanya.
Masih belum masuk di otak saya waktu kecil apa maksud puisi Sapardi Djoko Damono ini:
Di Kebun Binatang
Seorang wanita muda berdiri terpikat memandang ular yang melilit sebatang pohon sambil menjulur-julurkan lidahnya; katanya kepada suaminya, “Alangkah indahnya kulit ular itu untuk tas dan sepatu!”
Lelaki muda itu seperti teringat sesuatu, cepat-cepat menarik lengan istrinya meninggalkan tempat terkutuk itu.
1973
Banyak puisi para penyair terkemuka saya baca-baca saja, tetapi merasa tak senikmat membaca cerpen atau novel kala remaja di desa. Barulah ketika saya urban untuk meneruskan sekolah di SMAN 2 Bandar Lampung tahun 1986, saya mulai tertarik dan mulai coba-coba menulis puisi. Saya menemukan denyut kencang dunia kepenyairan di Kota Tapis Berseri ini.
Dari kliping koran Minggu yang saya langgani kala itu seperti Suara Karya, Merdeka, Media Indonesia, Berita Buana, Pelita, Swadesi, Simponi, Tamtama, dan Warta Niaga—Kompas tidak memiliki rubrik puisi–serta buku-buku antologi bersama seperti Parade Penyair Lampung (1986), Memetik Puisi dari Udara (1987), Gelang Semesta (1988), dan Pewaris Huma Lada (1988), termasuk beberapa kumpulan puisi tunggal, saya tahu—kenal sih belum—nama-nama penyair Lampung. Dari kalangan pelajar, ada Panji Utama, Ahmad Yulden Erwin, Pondi, Rojali, Affan Zaldi Erya, dan Iswadi Pratama.
Saat kelas dua SMA, saya mengetahui Panji Utama, Ahmad Yulden Erwin, dan Pondi menjadi redaktur majalah dinding (mading) sekolah. Mereka semua adik kelas saya. Ingin agar puisi saya dimuat, tetapi tak punya keberanian–atau bisa juga gengsi–saya titip beberapa puisi saya ke Emilia Zen, adik kelas juga di Smanda sesama orang Liwa, untuk mading. Entah kepada siapa di antara ketiga nama itu Emi memberikan naskah saya. Yang jelas, beberapa sajak di antaranya dimuat di mading.
Dengan nama Joel K. Enairy—yang di mading nama pena beda lagi–sajak-sajak saya pertama kali dimuat koran di Merdeka Minggu, 16 April 1989. Sejak itu saya semakin keranjingan menulis dan mengirim puisi ke berbagai media. Beberapa di antaranya dimuat.
Untuk Raden Intan, tabloid mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, saya menggunakan nama Z. Karzi. Sebagai jurnalis kampus di Universitas Lampung (Unila), saya gunakan Joel K. Enairy (JKE) untuk majalah Republica dan Z Karzi (ZKZ) untuk Surat Kabar Mahasiswa Teknokra.
Saya memang selalu berlindung di balik banyak nama samaran biar gak ketahuan kalau saya juga menulis puisi jelek seperti itu. Bahkan, mungkin Panji Utama, Iswadi Pratama, dan Ahmad Yulden Erwin yang mengeditori Daun-Daun Jatuh Tunas-Tunas Tumbuh, terbitan Surat Kabar Mahasiswa Teknokra tahun 1995, tidak tahu nama Z Karzi. Saya ingat, di ujung-ujung proses penerbitan, tiba-tiba Erwin ke redaksi.
“Ini naskah selip. Baru saya lihat. Masukkan ke buku,” kata dia memberikan beberapa lembar puisi karya Z Karzi.
Saya yang ada saya di situ menyambutnya.
“Jelek ya puisi-puisi ini?” tanya saya.
“Bagus kok!” tegas Erwin.
Alhamdulillah. Jadi juga puisi saya dimuat di buku untuk pertama kalinya.
Ya, inilah rugi… eh, untungnya pakai nama samaran.
Tapi, tak urung sekali waktu Lampung Post mencantumkan nama asli saya, Zulkarnain Zubairi, di sebuah puisi yang ia muat.
Nah, ketahuan!
Entah karena ketahuan (jeleknya), saya tak lagi banyak menulis sajak. Kalau terpaksa atau kepepet saja, barulah saya bikin (yang saya kira) puisi.
Ya, saya tak pernah hepi membaca puisi sendiri. Sebab, puisi penyair lain bagus-bagus.
Tapi, seburuk apa pun, yang tak seberapa itu aseli karya sendiri. Itulah yang sedikit bisa menghibur saya. Karena itu, kayaknya saya perlu mengumpulkan puisi-puisi yang terserak dan banyak yang hilang terbuang.
***
Sebagaimana saya tulis di “Manusia Terkutuk itu” dalam Teknokra, Jejak Langkah Pers Mahasiswa[1], saya sangat “frustasi” dengan puisi. Cinta ditolak justru karena sajak! Barangkali berlebihan. Tapi, saya merasa itulah yang benar terjadi.
Akibatnya, saya tak terlalu hirau lagi dengan yang namanya puisi, meskipun waktu kuliah saya sempat menjadi redaktur sastra di majalah Republica dan Surat Kabar Mahasiswa Teknokra.
Sampai kemudian saya membaca ada Sayembara Cipta Puisi Naratif Wisata-Budaya Lampung yang diselenggarakan dalam rangkaian Festival Krakatau 1999. Bagaimana sih puisi naratif? Saya buat saja sebuah prosa berjudul “Bagaimana Mungkin Aku Lupa”. Kepada Christian Heru Cahya Saputro sesama redaktur di Sumatera Post, saya berikan naskah ini.
“Bisa nggak?” saya tanya.
Mas Heru langsung menyambut dan meminta softcopy-nya. Ia poles sedikit, lalu bilang, “Ok, saya kirimkan. Ini juga saya mau mengirim.”
Dan, eehh, kok bisa menang sayembara. Sementara puisi orang yang memoles tidak.
Jadi semangat lagi menulis puisi. Tapi, malas. Gimanalah itu maksudnya.
Perkembangan selanjutnya, sebagai penutur bahasa Lampung, saya seperti “tersulut emosi” ketika ada wacana dalam sebuah seminar tahun 1999 juga bahwa bahasa Lampung akan punah dalam tiga-empat generasi atau 75—100 tahun lagi. Saya mulai menulis puisi berbahasa Lampung, dimulai dengan menerjemahkan sajak “Bagaimana Mungkin Aku Lupa” yang mempunyai banyak catatan kaki ke bahasa Lampung menjadi “Repa Nyak Dapok Lupa” sehingga catatan kaki tak diperlukan lagi. Puisi Lampung? Mana ada, kata ulun Lampung. Tapi, masih untung karena redaktur sastra Sumatera Post Panji Utama mau memuat puisi berbahasa Lampung saya. Begitu juga redaktur budaya Lampung Post Iswadi Pratama. Ia pun memuat beberapa puisi berbahasa ‘aneh’ itu di rubrik yang ia kelola. Setelah itu terbit tiga buku puisi berbahasa Lampung saya yang saya katakan di awal.
***
Agaknya, saya masih terbawa situasi memprihatinkan perihal kondisi bahasa dan sastra Lampung. Saya cenderung menahan diri untuk tidak menulis puisi dalam bahasa Indonesia. Saya lebih cenderung menggarap yang lokal-lokal Lampung, bahkan bahasa Lampungnya sekalian. Saya merasa berdosa karena saya tidak memiliki kemampuan melantunkan berbagai jenis—apa yang mereka sebut dengan—sastra tradisi Lampung atau sastra lisan Lampung. Satu-satunya yang saya warisi dari apa yang disebut adat-istiadat atau kebudayaan Lampung adalah bahasanya. Ya, bahasa Lampung. Saya cuma tukang tulis. Karena itu, saya menulis puisi dengan cara yang berbeda dari tradisi perpuisian bahasa Lampung yang sudah mapan.
Saya ngawur? Barangkali saja. Tapi, kreasi baru tentu saja mesti melawan yang sudah ada, menegasi yang telah mapan, dan melawan yang telanjur mentradisi. Saya hanya bertekad untuk memberdayakan, menggayakan, dan memberi tenaga pada bahasa Lampung dalam puisi Lampung. Kalau sebaliknya yang terjadi, saya malah dituding “merusak” bahasa (sastra) Lampung yang dianggap adiluhung; ya saya sudah pasrah saja. Biarin! Saya hanya tak mau berhenti menulis puisi Lampung.
Puisi bahasa Indonesia? Saya sudah “menyerah” sebenarnya. Apalah saya ini dibandingkan dengan para suhu dan siapalah saya di antara para penyair terkemuka di Lampung, di berbagai pelosok tanah air, apalagi di pelbagai belahan dunia.
Saya cuma mau menulis puisi Lampung.
Belakangan, saya berubah pikiran. Saya mulai menghimpun (yang saya anggap) puisi-puisi berbahasa Indonesia sejak 1987 hingga tahun ini, 2025. Agak sulit karena “sebundel puisi cinta dan patah hati” saya berikan kepada seseorang yang sempat menjadi tambatan hati, tetapi lebih memilih yang lain; sementara duplikatnya saya buang ke tempat sampah karena merasa apalah guna puisi ketika dihadapkan pada kenyataan hidup serbapragmatis serbamaterialis yang membuat saya tak berdaya.
Menyesal saya. Tapi, terlambat. Ketika saya tanya doi, apakah masih menyimpan jilidan puisi yang saya kasih ke dia doeloe, dia bilang, “Gak tahu disimpan di mana.”
Bisa jadi dibuang kali olehnya.
Beberapa puisi terpaksa direkonstruksi, “ditulis ulang” berdasar ingatan atas “puisi dari kumpulan yang terbuang”.
Maka, saya anggap “keajaiban” juga kalau 100 sajak berbahasa Indonesia berlini masa 1987–2025 ini bisa jadi dikumpulkan dalam satu buku.
***
Dalam proses penerbitan buku puisi ini, tiba-tiba menyeruak sebuah kontroversi dari rencana pemerintah menerbitkan ‘buku babon’ sejarah nasional pada Agustus 2025 kelak, sebagai ‘kado’ hari kemerdekaan RI ke-80. Menteri Kebudayaan Fadli Zon bilang buku ini adalah “revisi penambahan di buku sejarah” dan akan menjadi buku sejarah resmi Indonesia serta menjadi acuan buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah.
Meskipun Ketua Tim Penulisan Buku Susanto Zuhdi menjamin tak ada intervensi, sejumlah sejarawan menganggap ini akan menjadi alat legitimasi dan menghilangkan peristiwa “sensitif” tentang perempuan dan sejarah Papua. Arkeolog Truman Simanjuntak yang turut menyusun buku itu mengundurkan diri setelah menolak penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal” yang menurutnya, “menghapus istilah dan ilmu prasejarah dari nomenklatur keilmuan”. Sejarawan dari Papua Albert Rumbekwan menyayangkan hanya sedikit sejarah Papua ditampilkan. Padahal Papua punya sejarah panjang yang membentang paling sedikit sejak 500 tahun yang lalu. Sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya, Mohammad Refi Omar Ar Razy menyebut penyusunan buku ini terkesan terburu-buru, sementara isinya “masih sangat Indonesia sentris”, “sangat elite” dan tidak menyorot peran perempuan dalam sejarah Indonesia. Isinya tidak banyak memperbarui hal-hal yang fundamental dalam sisi historis.
Buku puisi ini jelas tak akan menjawab kontroversi penulisan ulang sejarah Indonesia. Namun, setidaknya penerbitan buku puisi ini memiliki cantelan peristiwa yang penting-tidak penting dan relevan-tidak relevan. Cuma sedikit refleksi mengenai perkembangan negeri.
Lalu, saya pun teringat ucapan Arifin C Noer (1941–1995), sastrawan dan sutradara film “Pengkhianatan G30S/PKI” menjelang akhir hayatnya yang ia sampaikan kepada adiknya, musikus Embie C Noer. “Ternyata, di dunia ini ada tiga orang besar. Ada orang besar karena dia sibuk mencatatkan diri dalam sejarah. Ada orang besar karena dia ‘koar-koar’. Dan ada orang besar karena karyanya. Berkarya saja, jangan cari efek,” kata Arifin.
***
Terima kasih kepada Penyair Doddi Ahmad Fauji atas kesediaannya memberikan pengantar untuk buku ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memungkinkan lahir kembali anak ruhani saya ini.
Dan yang utama, terima kasih dihaturkan kepada istri tersayang Reni Permatasari yang harus memiliki segudang kesabaran menghadapi “kelakuan tak lumrah” suaminya serta anak-anak M Aidil Affandy Liwa dan Raihan Herza Muzakki Liwa yang kini sudah menjadi “lawan” dan “kawan” bagi ayah mereka dalam berbagai “kerusuhan” di rumah.
Tabik. []
Wismamas Kemiling, Februari 2025
[1] Budisantoso Budiman & Udo Z Karzi (Ed.). 2010. Teknokra, Jejak Langkah Pers Mahasiswa. Bandar Lampung: Teknokra.





