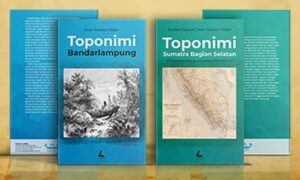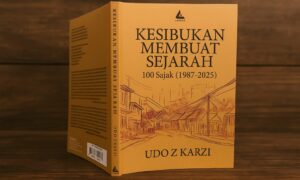Menyoal Kesalehan di Era Digital
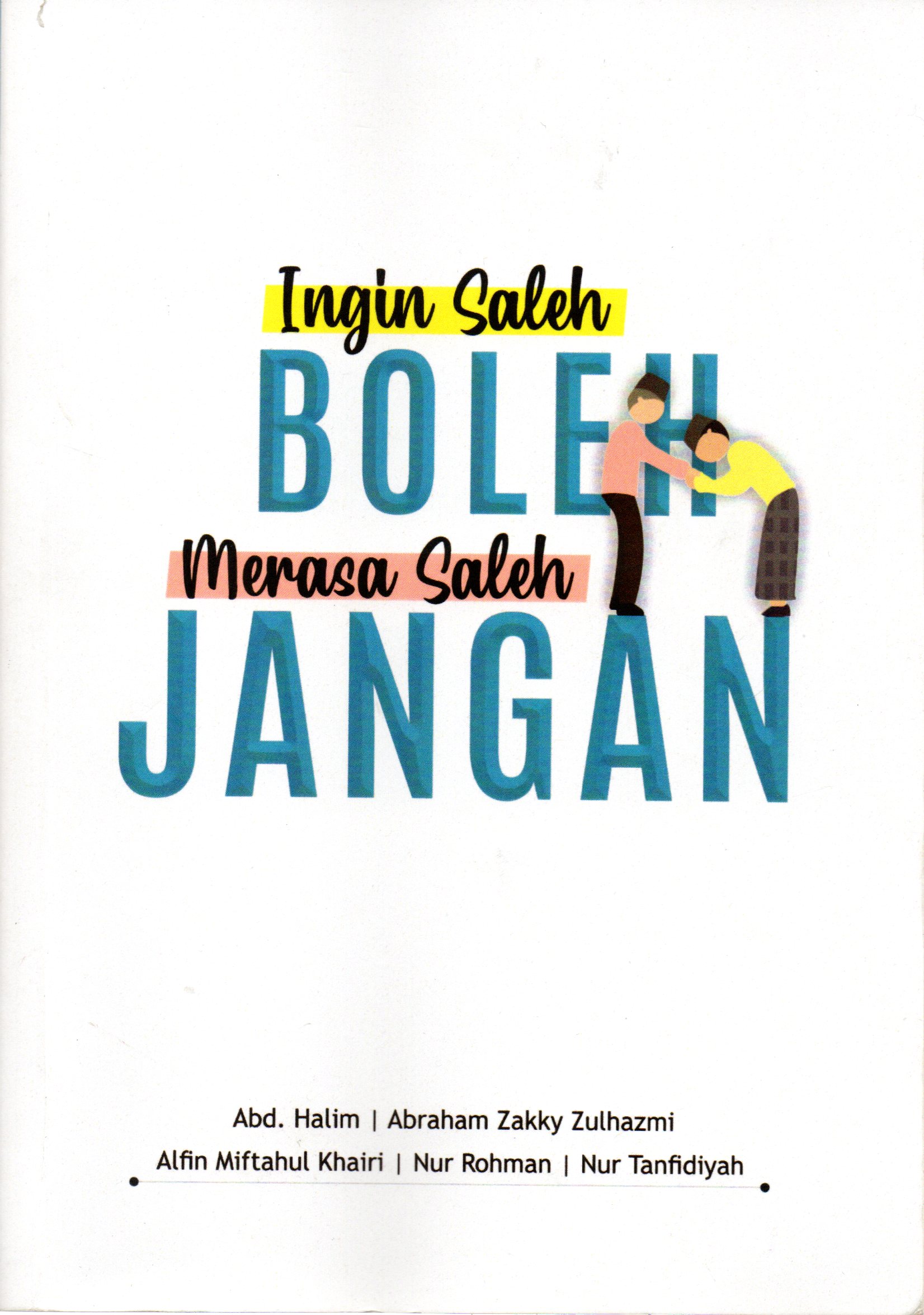
Oleh Adib Baroya Al Fahmi
Judul buku: Ingin Saleh Boleh, Merasa Saleh Jangan. Penulis: Abd. Halim, dkk. Penerbit: Sulur
Cetakan: I, Mei 2020. Tebal: 234 halaman. ISBN: 978-602-5803-871.
RUANG-RUANG media maya telah membentuk wajah peradaban jadi serba cepat, instan, dan terkoneksi atas jejaring dunia tanpa batas. Perkembangan teknologi menghendaki rekaan dunia sosial melalui keberadaan internet. Mengutip Mujibburrahman tentang penyakit generasi elektronik di Sentilan Kosmopolitan (Kompas, 2013) bahwa, “paling kurang ada tiga kecenderungan negatif yang kini mulai tampak dalam perilaku masyarakat kita, yaitu kecanduan, penyalahgunaan, dan pamer.”
Media elektronik, sebagaimana alat komunikasi nyatanya menyimpan sisi baik dan buruk. Yang pasti, butuh pemahaman agar dapat memakai perangkat elektronik secara bijaksana dan tepat guna. Selain agar mampu memilah-milih informasi yang mesti dibaca lalu dibagikan. Hal inilah yang menjadi masalah gawat. Saat gawai semakin mudah didapat-gunakan, dan dunia kian terlipat dalam genggaman. Cukup beberapa sentuhan saja, semua sudah terhidang di depan mata.
Tak bisa kita pungkiri memang, semua telah beralih pada dunia yang serba digital. Kita malah jadi enggan, atau minder mendalami literatur keaksaraan agama guna mencari jalan terang dan pemahaman. Sebab, segala hal toh sudah ada di internet. Kebebas-leluasaan yang ditawarkan internet justru menjadi oposisi ampuh dalam menyerang pengetahuan yang sudah (lama) mapan.
Sungguh, tak satupun sektor kehidupan yang tak tersentuh jari-jari teknologis ini. Semua turut berdampak terhadap cara pandang, sikap, pemahaman terhadap ilmu-pengetahuan, bahkan anasir dunia. Termasuk juga “ikhtiar” dalam merengkuh agama ataupun spiritualitas sendiri. Fenomena keagamaan mutakhir ini jadi sorotan pokok dalam buku Ingin Saleh Boleh, Merasa Saleh Jangan (2020).
Buku sehimpun esai ini mengajak pembaca untuk merasa peka dan merefleksikan kembali laku sosial-keagamaan sehari-hari. Apalagi, keadaan zaman tengah berada pada ambang disrupsi. Sejenak melakukan refleksi dan kontemplasi tentulah cukup penting. Sekian esai dalam buku ini menyinggung fenomena sosial, kultural, politik, pendidikan-pengajaran, identitas, tasawuf, seni, hingga ekologi.
Abraham Zakky Zulhazmi, lewat esai Belajar Agama Online dan Hantu Terorisme misalnya, menyebut bahwa metode mendalami agama secara daring makin digandrungi. Jalan mempelajari agama semacam ini kerap ditempuh karena godaan akan kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan. Internet telah melipat jarak dan segalanya ke dalam gawai.
Hal semacam itu seolah makin diamini dengan maraknya model pembelajaran-pengkajian yang mengandalkan ceramah di media sosial secara sepintas dan teks-teks singkat. Ceramah-ceramah di internet cepat muncul dan berlalu. Terlebih lagi, ramainya dakwah-sebagian kelompok-yang acap menebar isu sensitif terhadap golongan tertentu. Dakwah semacam ini kerap memakan korban, yakni kaum minoritas. Kenyataan tadi semakin memperkeruh suasana keberagama(a)n kita.
Takdir negara-bangsa Indonesia yang majemuk dan plural ini selayaknya menjadi kekuatan tersendiri. Bukan malah jadi ajang adu domba, perebutan kekuasaan, dan kepentingan praktis-ideologis lainnya yang mengancam kebhinekaan kita. Iklim keragaman dapat menjadi kawah candradimuka untuk sama-sama saling merangkul dalam simpul harmoni. Kita masih bisa percaya pada solidaritas dan tali ukhuwah.
Narasi Ekstrimisme
Adapun dakwah termasuk perbuatan yang mulia. Sejatinya, dakwah bermaksud untuk mengajak seseorang ke jalan yang lurus demi mendapat ridha Sang Illahi. Ajakan demi ajakan sebaiknya mampu mengingatkan sekaligus memberi percikan kesadaran, bukan malah menjauhkan diri dari orang lain dan memutus tali persaudaraan Ketidaksudian untuk membaca-memahami orang lain ini, sering-untuk menyebutnya tidak “selalu”-berakhir dengan fanatisme buta.
Fanatisme yang sudah terlampau sangat mampu menenggelamkan nalar kritis dan menyurutkan keterbukaan untuk berdialog secara egaliter. Sehingga, akan membentuk garis demarkasi antara yang merasa diri saleh, dengan di sisi lain adalah tempat yang dianggap tidak saleh.
Selain itu, kita sudah sering melihat bahwa, dari internet semua bisa bermula. Dunia internet jadi labirin yang memiliki banyak lorong. Zakky menganggap saat berselancar di internet, alangkah baiknya bila membawa obor penerang agar tetap selamat. “Saya selalu mengibaratkan berselancar di internet dan sosial media adalah seperti hutan yang luas dan lebat pada malam hari. Tanpa membawa obor sebagai penerang, mereka bisa terperosok ke jurang, jatuh ke akar pohon, bahkan diterkam hewan buas,” tulis Zakky. (hlm. 80)
Tak hanya persoalan ideologi radikal, tetapi juga ekstrimisme yang turut mengisi dinding media sosial kita. Alfin Miftahul Khairi dalam esai Remaja dan Bahaya Ekstrimisme mencatat bahwa remaja gampang sekali terpapar paham radikal. Kalangan remaja yang sedang mencari jati diri pun rentan mendapat seruan jadi relawan radikalis.
Alfin berangkat dari warta penangkapan terorisme di Bekasi, Solo, dan peristiwa pengeboman di Sri Lanka. Pelaku dari tiga peristiwa menggegerkan itu adalah sama-sama pemuda. Lalu, Alfin memberi kritik dengan representatif, “Semangat mempelajari agama Islam yang tinggi tidak dibarengi dengan guru yang tepat dan sumber rujukan atau referensi keilmuan yang jelas… Justru menjadi makanan empuk bagi mereka (teroris) untuk merekrutnya. Seolah-olah mereka adalah dewa penolong menuju jalan yang benar.” (hlm. 140)
Dilihat sepintas, terorisme mempunyai sikap keagamaan yang mirip dengan kelompok fundamental. Karakteristik terorisme, seperti penjelasan Hisanori Kato lewat buku Islam di Mata Orang Jepang (Kompas, 2014) adalah keinginan meraih tujuan dengan alat kekerasan. Perbedaan terorisme secara umum dengan terorisme agama, yaitu terorisme agama memiliki pedoman “diberkati dan diampuni Tuhan”.
Semua bisa terjadi, bermula dari niat memperdalam agama. Gelora mempelajari agama yang tinggi memang baik. Namun alangkah lebih tepat jika belajar agama kepada sumber (sanad) yang betul-betul jelas. Alfin mendudukkan perkara ini sebagai tanggapan dan peringatan. Di sinilah letak urgensi yang diserukan Alfin.
Maka, buku ini pantas dibaca untuk mengingatkan diri dalam menjaga kesalehan, di tengah gelombang pasang modernisasi yang semakin digital. Agar laku beragama tidak hanya saleh secara ritual, sosial, tetapi juga saleh secara virtual. []
—————————-
Adib Baroya Al Fahmi, Mahasiswa IAIN Surakarta. Nimbrung di komunitas Serambi Kata, Solo.